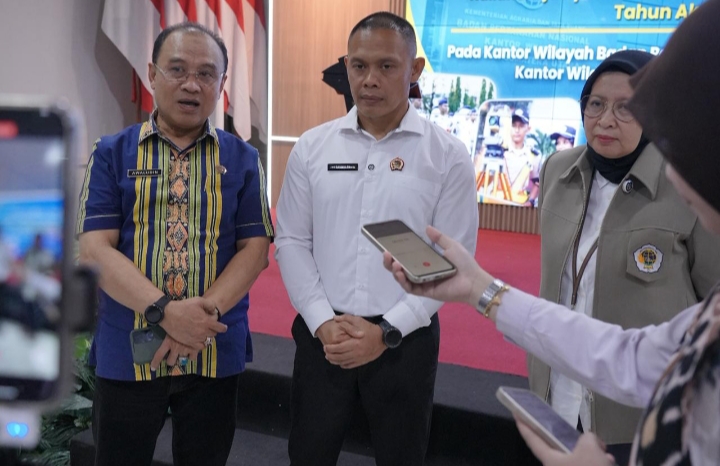Wartawan Iyus Firdaus
Pelitasukabumi.id– Polusi plastik kini menjadi salah satu ancaman nyata yang memperburuk krisis lingkungan global. Dunia tidak hanya diguncang persoalan ekonomi, tetapi juga dihadapkan pada tiga krisis ekologis yang saling berkaitan erat yaitu perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan polusi.
Ketiganya mengancam keberlangsungan hidup manusia dan bumi, dengan plastik sebagai salah satu faktor pemicunya yang paling dominan. Tak heran jika tema Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2025 menyoroti isu ini dengan tajuk “Hentikan Polusi Plastik”.
Sampah plastik kini menyusup ke berbagai aspek kehidupan dan lingkungan. Plastik yang bocor ke alam mengakibatkan kerusakan pada ekosistem darat maupun laut. Flora dan fauna menjadi korban, baik secara langsung maupun melalui akumulasi jangka panjang.
Parahnya lagi, kerusakan ekosistem penyerap karbon seperti mangrove turut mempercepat kenaikan suhu bumi memperkuat dampak perubahan iklim yang sudah terasa di berbagai belahan dunia.
Di Indonesia, sampah plastik menduduki peringkat kedua dalam komposisi sampah nasional. Berdasarkan data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), dari 34,2 juta ton sampah pada 2024 yang tercatat di 317 kabupaten/kota, sebanyak 19,74 persen di antaranya merupakan plastik.
Ini menunjukkan peningkatan signifikan dari 11 persen pada 2010. Artinya, plastik terus merangsek menjadi masalah struktural dalam sistem pengelolaan sampah nasional.
Tidak seperti sampah organik yang mudah terurai, plastik bersifat resisten terhadap waktu. Plastik bisa bertahan selama belasan hingga puluhan tahun di alam, dan ketika mulai terdegradasi, partikel-partikelnya berubah menjadi mikroplastik dan nanoplastik.
Partikel ini memasuki rantai makanan, menumpuk dalam tubuh manusia dan hewan, dan berpotensi menimbulkan masalah kesehatan yang serius dalam jangka panjang.
Masalah ini juga memiliki dimensi global karena sampah plastik adalah polutan lintas batas. Banyak ditemukan plastik bertuliskan “made in Indonesia” di pesisir negara lain, dan sebaliknya.
UNEP bahkan mencatat bahwa pada 2020 sebanyak 9 hingga 14 juta ton plastik masuk ke lautan dunia, yang diperkirakan melonjak menjadi hingga 265 juta ton pada 2060.
Sementara penelitian BRIN menunjukkan bahwa 10 hingga 20 persen sampah dari Indonesia bisa hanyut ke perairan internasional, bahkan sampai ke Afrika Selatan dalam kurun waktu setahun.
Kerugian akibat pencemaran plastik bukan hanya ekologis, tetapi juga ekonomis. BRIN memperkirakan sekitar 484 ribu ton sampah plastik bocor ke laut setiap tahun dari Indonesia, dengan nilai kerugian ekonomi mencapai Rp25 hingga Rp255 triliun per tahun.
Kerugian ini mencakup potensi sektor pariwisata, perikanan, dan kerusakan infrastruktur akibat sampah yang tidak tertangani. Pemerintah Indonesia mulai mengambil langkah lebih tegas sejak Presiden Prabowo dilantik akhir 2024.
Kementerian Lingkungan Hidup kini memfokuskan diri pada penanganan sampah, termasuk menghentikan impor bahan baku daur ulang dan menindak tempat pemrosesan akhir (TPA) yang masih melakukan open dumping.
Sudah ada 343 TPA yang dijatuhi sanksi administratif, bahkan beberapa diproses hukum, seperti Unit Pengelolaan Sampah Terpadu Bantargebang.
Namun, langkah-langkah itu tidak selalu mudah. Penutupan TPA open dumping memicu penolakan warga di beberapa daerah, seperti yang terjadi di Banjarmasin hingga muncul gugatan class action.
Di sisi lain, pemerintah mempercepat pembangunan fasilitas teknologi seperti Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di 33 titik dan fasilitas RDF (Refuse Derived Fuel), meski beberapa menghadapi penolakan masyarakat seperti di Rorotan, Jakarta.
Solusi teknologi akan sulit berjalan tanpa perubahan perilaku masyarakat. Tragedi TPA Leuwigajah pada 2005 yang menewaskan 157 orang pun belum cukup menggugah kesadaran publik secara luas.
Padahal, Indonesia sudah memiliki payung hukum berupa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Yang dibutuhkan saat ini adalah kepatuhan terhadap aturan, pengawasan, edukasi publik, dan tanggung jawab individu yang nyata.
Contoh keberhasilan dapat dilihat dari pelarangan kantong plastik di beberapa kota.Aturan ini diikuti oleh dunia usaha dan didukung oleh kebiasaan baru warga. Survei Populix pada 2023 mencatat bahwa 80 persen responden kini membawa tas belanja dan botol minum sendiri.
Ini menunjukkan bahwa sinergi antara aturan, pengawasan, partisipasi dunia usaha, dan perubahan gaya hidup masyarakat bisa menjadi pola keberhasilan. Bila pola ini diperluas, target pengelolaan sampah 100 persen pada 2029 sesuai Perpres Nomor 12 Tahun 2025 bukan sekadar ambisi, melainkan masa depan yang bisa diwujudkan.